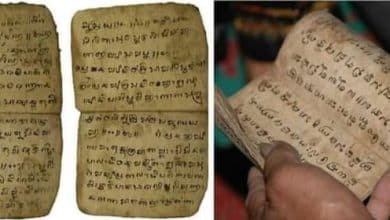Tidak banyak tokoh politik semujur Anas Urbaningrum. Ia dipenjara sekian tahun, dan ketika keluar disambut oleh ratusan massa pendukung, sahabat atau sekadar simpatisan. Sebagian penyambutnya datang dengan aneka atribut HMI, seakan Anas identik dengan HMI dan seolah ia dihukum dalam konteks ke-HMI-an. Dan ia diminta berpidato di hadapan forum langka itu.
Panggungnya kuat: halaman penjara Sukamiskin, Bandung; tempat yang seabad lalu juga menjadi tempat penyekapan Bung Karno. Massa yang menyambutnya ingin mendengar pernyataan Anas setelah lebih dari delapan tahun mereka tak mendengar sepatah kata pun dari dia.
Dan Anas Urbaningrum, yang terbelit kasus hukum dalam posisi sebagai ketua umum partai terbesar yang sedang berkuasa waktu itu, tidak memanfaatkan momen itu dengan baik.
Mungkin ia tidak menyadari magnitude peristiwa itu dari segi politik. Karena itu ia tak merasa penyajian pidato alakadarnya di sana merupakan kemubaziran yang patut disayangkan.
Dari 17 menit lebih durasi video yang beredar tentang peristiwa itu, saya hanya sanggup menontonnya kurang dari separuhnya. Isinya sepenuhnya formalitas, ucapan terima kasih kepada para penyambut dan teman-teman yang ia tahu bersimpati kepadanya, meski tak ikut hadir. Terima kasih juga kepada “Bapak Kalapas dan jajarannya yang selama ini telah membina kami..”
Ia bilang: “Meskipun saudara-saudara semua berkumpul di halaman penjara ini, tapi percayalah, saudara-saudara semua, juga teman-teman yang tak hadir, bukan berada di halaman hati saya, melainkan selalu berada di relung-relung hati saya yang terdalam.” Sebuah metafora yang cukup puitis — a bit cheapy-poetic.
Terlepas dari rincian kasus hukumnya, yang telah sangat banyak dibahas sepuluhan tahun silam beserta aneka drama dan kontroversinya, ia selayaknya menggunakan kesempatan langka itu dengan sebaik-baiknya; yaitu menyampaikan pikiran-pikiran yang bermakna dalam konteks politik maupun kemanusiaan.
Apa arti berada di penjara, selama waktu yang cukup panjang, baik sebagai warganegara, sebagai manusia, sebagai politisi? Hasil renungan semacam itulah yang pertama-tama perlu ia sampaikan kepada massa penyambut maupun publik luas yang ikut menyaksikan videonya.
Ia bisa membingkainya dengan makna kebebasan dan ketidakbebasan. Dengan itu ia bisa memberi inspirasi kepada publik.
Inspirasi — inilah memang kata kuncinya.
Apa yang ia akan lakukan sejak hari pertama ia bebas, dalam konteks profesinya sebagai politisi? Bagaimana penilaiannya terhadap politik Indonesia, seperti yang ia amati dari dalam penjara? Tidak mungkin ia tak mencermati dinamika politik dari balik dinding Sukamiskin. Ulasan dan penilaiannya, sebagai mahasiswa ilmu politik maupun eks pemimpin partai besar, perlu ia sampaikan kepada publik.
Ada cukup banyak contoh untuk itu. Pertama, yang sangat dekat dengan pengalaman politik kita, pidato Presiden Sukarno. Di Afrika Selatan ada Nelson Mandela. Di Korea Selatan ada Kim Dae-Jung (pemimpin Partai Demokrat), yang divonis hukuman mati; lalu jadi presiden dan meraih Nobel Perdamaian.
Baru dua tahun lalu ada Alexei Navalny di Moskow. Dari masa yang lebih jauh, di Italia Antonio Gramsci bahkan muncul dengan buku kecil “A Prison Notebooks”, yang bahkan meyajikan teori tentang hegemoni serta fungsi dan peran intellegentsia, yang masih sering dikutip kalangan sayap kiri sampai sekarang.
Mereka semua sama: menyampaikan sesuatu yang bermakna, dari segi politik — renungan personal maupun publik — dan dimensi-dimensi yang lebih luas, sekeluarnya dari penjara (Gramsci dihukum 20 tahun penjara pada 1926, dan meninggal di dalamnya pada 1937). Meski kasus-kasus mereka berbeda dari kasus Anas, ia bisa memetik inspirasi dari pidato-pidato mereka (paling sedikit karena kesamaan konteks).
Sebuah pidato politik, bahkan dalam situasi normal, mestinya memuat pernyataan dan argumen yang gamblang, yang mampu membangkitkan inspirasi pendengarnya untuk melihat sesuatu dengan cara baru; atau bertekad untuk melakukan tindakan tertentu. Statemen-statemennya harus punya daya sentuh emosional dan kekuatan pengimbau nalar.
Sayang sekali Anas Urbaningrum tidak memanfaatkan kesempatan penting itu. Ia memilih cara lain — yang membuat kita hanya mampu menyayangkannya. *