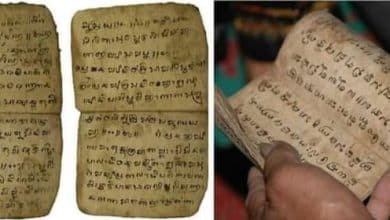Gen-Z dan Kapitalisme: Melawan dengan Cara Kapitalistik
Oleh: Harul Mukri Ananta (Mahasiswa Pendidikan Sejarah UNP)
Generasi Z—anak-anak yang dibesarkan dalam pelukan Wi-Fi—akrab betul dengan kapitalisme, bukan sebagai sistem ekonomi belaka, tapi sebagai gaya hidup, bahkan estetika. Kapitalisme bagi Gen-Z bukan lagi soal eksploitasi buruh pabrik dan perusahaan multinasional rakus.
Ia sudah berakulturasi menjadi budaya pop; dikemas dalam bahasa “productivity is sexy” dan “your hustle defines your worth.” Sexy? Mungkin. Menyesatkan? Bisa Jadi. Gen-Z dan kapitalisme tampak seperti pasangan aneh.
Jelas ini menciptakan paradox. Di satu sisi, Gen-Z vokal soal keadilan sosial, lingkungan, dan isu mental health. Mereka berdemo virtual, membuat petisi online, dan membangun komunitas digital yang kritis. Tapi di sisi lain, mereka tetap antre beli iPhone atau tergoda dengan promo flash sale. Kontradiktif? Ya. Tapi juga sangat manusiawi. Mereka sedang bernegoisasi—antara idealisme dan realitas hidup yang mahal.
Mereka menjadikan kapitalisme sebagai bahan meme, bahan dagangan, dan bahan refleksi diri. Begitulah bentuk perlawanan di era sekarang: melawan kapitalisme dengan cara kapitalistik. Gen-Z bukan generasi yang lahir dari revolusi, melainkan adaptasi.
Kapitalisme bukan disikapi sebagai musuh bebuyutan, melainkan partner yang toxic tapi sayang. Mereka menyadari bahwa sistem ini tidak ideal, tapi mereka juga tahu bahwa bertahan hidup di dunia sekarang butuh akal, bukan idealisme murni. Bayangkan: kapitalisme adalah sistem yang mengajarkan bahwa “dirimu adalah merek.” Nah, Gen-Z tidak menolak itu.
Mereka malah rebranding dirinya jadi konten—personal branding jadi senjata, dan kreativitas jadi mata uang baru. Ini bukan sekadar adaptasi, ini evolusi cara hidup di era pasar bebas yang lebih cair dan simbolik. Jadi, Apakah Kontradiktif? Mungkin lebih tepat disebut paradox eksistensial.
Di satu sisi melawan sistem, di sisi lain hidup darinya. Seperti menyetir mobil sembari mengkritik bahan bakarnya. Tetapi saya ingin mengupas lebih dalam, bagaimanapun akulturasi budaya di bawah tekanan sistem besar itu bukan hal yang baru. Gen-Z dan kapitalisme hanyalah versi kekinian dari pola lama: budaya lokal bertemu kekuatan besar, lalu beradaptasi—kadang dipaksa, kadang sukarela, kadang setengah sadar.
Zaman Kolonial: Pertemuan dengan Imperialisme Dulu, ketika bangsa-bangsa Eropa datang dengan senjata dan dagangan, masyarakat lokal—termasuk di Nusantara—tidak sertamerta melawan total atau menerima total. Mereka mengakulturasi, Islam dan Kristen bisa berdampingan dengan tradisi animisme; batik tetap hidup meski pasar dikuasai tekstil pabrik. Kita tidak membuang budaya lama, tapi mengemas ulang dengan cara baru.
Masuknya sekolah Belanda tidak membuat semua pribumi jadi pro-kolonial. Malah pribumi menggunakan pendidikan Barat untuk melawan Barat. Era Orde Baru: Modernisasi Gaya Soeharto Modernisasi yang dicanangkan negara— dengan wajah kapitalistik dan sentralistik—tidak membuat budaya lokal mati. Rakyat menyesuaikan. Adat-istiadat dijadikan festival untuk turis, dan “pembangunan” jadi kata suci. Di balik itu, perlawanan harus tetap ada: lewat lagu, sastra, bahkan dagelan seperti Srimulat. Sama halnya, Gen-Z tak sepenuhnya takluk pada kapitalisme. Mereka justru mengolahnya jadi alat.
Bukan sekadar konsumen, mereka produsen identitas. Kapitalisme diambil sebagian, dikritik sebagian, dan dipermainkan dengan estetika meme, ironi, dan konten. Apa yang dilakukan Gen-Z hari ini bukan penyerahan, tapi strategi bertahan. Jangan terburuburu menyalahkan. Mereka bukan pemberontak klasik, tapi creator taktis.
Mereka tahu bahwa dunia yang dikendalikan algoritma dan branding, cara terbaik bertahan adalah menjadi bagian darinya—sembari mencubit sistem dari dalam. Jadi, akulturasi Gen-Z dan kapitalisme bukan kontradiksi yang kaku, tapi paradoks yang cair. Mereka menari di atas panggung yang dibangun kapitalisme, tapi dengan gerakan mereka sendiri. Ironis, tapi juga penuh harapan. Selama dunia belum berubah, barangkali—scroll TikTok sembari merancang revolusi.
Sejarah mengajarkan: budaya tidak mati, ia beradaptasi. Mereka tumbuh dalam dunia di mana batas antara kritik dan partisipasi kabur. Menggunakan kapitalisme bukan berarti tunduk padanya. Justru dalam penguasaan tools kapitalisme—media sosial, tren, algoritma—mereka menyelipkan narasi tandingan.
Seperti seniman avant-garde, Gen-Z mengekspresikan keresahan lewat format-format yang bisa viral: tweet sarkastik, reels bernuansa dekonstruktif, atau bahkan merchandise bertema anti-kapitalis yang dijual secara kapitalistik. Lucu? Iya. Tapi juga sangat efektif. Kapitalisme di tangan Gen-Z bukan ideologi final, tapi kanvas.
Mereka menggambar ulang makna hidup, kerja, dan eksistensi di atasnya. Mereka sadar bahwa sistem tidak bisa ditumbangkan dalam semalam, jadi yang bisa dilakukan adalah menyusupinya—membajak maknanya, menyelewengkan tujuannya, mengubah dari dalam. Strategi ini bukan pengkhianatan terhadap idealisme, melainkan bentuk baru dari resistensi: subtil tapi konsisten. Jika generasi sebelumnya membawa spanduk dan orasi, Gen-Z membawa caption dan filter.
Tapi pesannya tetap sama: dunia ini bisa diubah. Hanya saja, caranya kini berbeda. Dan mungkin, justru lewat caranya itu mereka sedang menulis bab baru dalam sejarah perjuangan— dengan gaya, dengan kreativitas, dan dengan banyak tab browser terbuka.