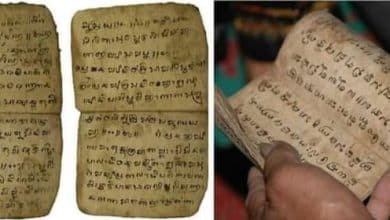Oleh : SYAMSUL BAHRI,SE
Demokrasi Pilkada sejatinya adalah sistem yang menjamin setiap orang dalam konteks hak berpolitik, memiliki hak dasar untuk memilih dan dipilih. Karena itu, dalam demokrasi, sistem kepemimpinan diharapkan berjalan dinamis dimana hanya mereka yang mampu merebut hati rakyat lewat rencana program-programnya lah yang akan terpilihm melalui penyampaian visi dan misi.
Namun sering kali system yang sudah terbentuk ini dalam implementasinya tidak bisa berjalan dengan baik dan ideal. Dan kita sudah banyak memantau dalam banyak kasus di Perpolitikan kita sistem kepemimpinan dikuasai oleh dinasti tertentu yang memiliki sumberdaya politik, sumberdaya uang dan juga sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya politik dan lainnya, yang menyebabkan system tidak lagi menjadi system yang baik dan sehat.
Sehingga Dinasty politik yang didefenisikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga (Wikipedia). Dinasti politik lebih indentik dengan kerajaan, sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak. agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga, swalaupun secara hokum bukan merupakan sebuah pelanggaran.
Namun secara hukum legal aspek, politik Dinasti memang bukan merupakan politik yang melanggar hukum atau ketentuan dan syah-syah saja dalam negara demokrasi seperti Negara Demokrai di Indonesia, hal ini secara hukum telah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) saat menghapus pasal ‘dinasti politik’ dalam UU No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Dalam Pasal 7 huruf r disebutkan: Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota adalah yang memenuhi persyaratan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.
Pada kalimat tersebut ada penggalan kata “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” yang dimaksud disini adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 kali masa jabatan.
Pasal ini dihapus oleh Mahkamah Konstitusi karena pemaknaan dinasti politik itu hanya mempertimbangan aspek HAM dan aspek yuridis yang bertentangan dengan dengan konstitusi dan UUD 1945, namun tidak mempertimbang dampak dan konsekwensi dari perbolehan Politik Dinasti ini berjalan bagi keutuhan sebuah tujuan demokrasi untuk mewjudkan keadilan social bagi seluruh Indonesia, yang menafikan kenyataan di mana kepala daerah petahana (incumbent) memiliki berbagai keuntungan. Namun, pembatasan demikian haruslah ditujukan kepada kepala daerah petahana itu, bukan kepada keluarganya, kerabatnya, atau kelompok-kelompok tertentu tersebut,” putus MK dalam sidang terbuka untuk umum pada 8 Juli 2015.
Sehingga dengan jelas dalam putusan itu, MK secara tegas mempertimbangkan hak konstitusional warga untuk memilih dan dipilih (right to be vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional.
Dengan adanya putusan MK maka sejarah politik dinasti akan terulang karena belum bisa dipangkas dengan baik, karena pasal yang dibatalkan MK bisa memotong rantai politik dinasti di daerah.
Politik Dinasti dari aspek etika, maka Politik Dinasti sangat tidak baik, karena akan terjadi tingkat kerawanan politik baik pra pilkada maupun pasca pilkada dan dalam kekuasaan, karena kecenderungan memang kebijakan dinasti ini menyuburkan salah satunya adalah KKN (Koncoisme, korupsi dan Nepptisme), dan kecenderungan pra pilkada akan menggunakan semua fasilitas kekuasaan untuk mendapatkan kemenangan dalam suatu proses pilakada, termasuk infrastruktur Politik itu sendiri, begitu juga pasca pilkada akan lebih parah lagi.
jika kita simak tulisan Oleh Pudjo Rahayu Rizan Selasa, 24/12/2019 pada berita on line antara dengan judul Pro kontra politik dinasti “pada kontek pro dan kontrak politik dinasti pemaknaan demokrasi menimbulkan dua pemahaman yang saling bertentangan yaitu politik dinasti tidak bertentangan dengan demokrasi, tapi disisi lain sering melanggar dari prinsip demokrasi itu sendiri”, selanjutnya ditegaskan lagi, apakah politik dinasti mengkebiri demokrasi dengan jawaban bisa ya bisa tidak, karena politik dinasti cenderung mempengaruhi proses yang semestinya demokratis menjadi tidak demokratis, karena campur tangan pihak-pihak yang memegang kekuasaan, kekuatan, pengaruh, infrastruktur politik, bungkusnya demokrasi, tapi isinya bukan demokrasi.
Data dari Kementerian Dalam Negeri (Politik dinasti, anomali demokrasi, melalui beritagar.id 14/10/2017) menyebutkan pada tahun 2016 terdapat tidak kurang dari 60 dinasti politik yang tersebar di seantero Indonesia. Yang paling populer tentu dinasti politik Ratu Atut di Banten. Kasus Ratu Atut barangkali hanyalah semacam fenomena gunung es. Di daerah-daerah yang jauh dari ibukota dan luput dari pemberitaan, dinasti politik tumbuh subur menjadi musuh ancaman bagi masa depan demokrasi Indonesia.
Memang diakui Sistem demokrasi saat ini dengan system OMOV (one man one vote) terbuka, setiap pemilih dihargai dengan satu suara memungkinkan bagi tumbuh suburnya politik dinasti, apalagi dikaitkan dengan kemiskinan dan Pendidikan suatu daerah, sehingga politik dinasti akan berkembang dengan suburnya.
Jika kita semak dan kita fahami ciri demokrasi akan dicirikan dengan 3 kekuasaan, pertama yaitu pembagian kekuasaan trias politika yakni eksekutif, yudikatif dan eksekutif, yang bertujuan agar kekuasaan tidak menumpuk pada kekuasaan eksekutif semata-mata, agar terjadi proses check and balances antar lembaga pemerintah.
Kedua terlaksananya suksesi kepemimpinan dengan baik dan demokratis dan terbuka melalui mekanisme Pemilu yang bersifat Jurdil dan Luber mekanisme pemilihan umum yang adil, jujur dan terbuka
Ketiga adalah kedaulatan ada ditangan rakyat, namun nyatanya kedaulatan ditangan rakyat cenderung tidak sepenuhnya, karena kedaulatan sebagain besar ada di tangan Partai Politik berdasarkan Parlemen threshold.
Dengan maraknya dinasti politik, tiga pilar demokrasi itu berada dalam ancaman besar, sistem check and balances dipastikan tidak akan berjalan efektif manakala semua lini dikuasai orang-orang yang sekerabat. Pembahasan yang bersifat kesejahteraan rakyat sedianya menentukan hajat hidup orang banyak justru lebih mirip arisan keluarga, jika demikian maka ucapkan Selamat tinggal politik dinasti.
Begitu pula dalam soal suksesi kepemimpinan yang adil dan terbuka, sesungguhnya mustahil hal itu bisa terwujud jika jabatan-jabatan politis dan jabatan structural akan digilir dan diperebutkan oleh orang-orang yang masih dalam lingkaran trah keluarga. Seperti yang terjadi di beberapa daerah, jabatan bupati diisi oleh suami sementara sang istri jadi wakil. Ketika suami sudah menjalani masa dua periode, sang istri pun mencalonkan menjadi bupati. Politik dinasti lebih mirip seperti lingkaran setan yang tiada ujungnya.
Etika politik menurut Franz Magnis Suseno (Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern) bahwa fungsi etika politik terbatas pada upaya menyediakan seperangkat teori untuk mempertanyakan dan menjelaskan kekuasaan politik secara bertanggung jawab.
Untuk menjadi seorang pemimpin mutlak dituntut punya pemahaman yang sahih tentang etika politik, karena politik bukanlah alat meraih kekuasaan semata-mata, melainkan alat untuk mewujudkan tata kehidupan yang adil, damai dan sejahtera dan jika Politik yang dipahami sebagai alat untuk meraih kekuasaan niscaya terjebak dalam kompetisi meraih dan mempertahankan jabatan, dengan menghalalkan segala cara.
Politik yang seperti itu, dalam implementasinya dipastikan abai pada norma dan etika politik, maka sewajarnya politik praktis identik dengan konspirasi, intrik, konflik bahkan perilaku-perilaku koruptif.
Banyaknya bukti konkrit praktik Politik Dinasti terutama pada Pemilu Kepala Daerah yang membangun dinasti politik dan kemudian terjerat kasus korupsi adalah contoh nyata bagaimana politik dinasti lekat dengan penyelewengan kekuasaan.
Politik Dinasti ini diakui merebak dan berkembang dalam Demokrasi di Indonesia sebagai sebuah manifestasi dari absennya etika politik di pentas politik, terutama di level daerah. Demokrasi Pilkada pada Otonomi daerah yang sedianya bertujuan memeratakan hasil pembangunan justru melahirkan raja-raja kecil yang menjadikan kekuasaannya sebagai alat memperkaya diri sendiri dan kerabatnya.
Memang politik dinasti ini secara hukum merupakan sebuah implementasi yang tidak melanggar hukum, karena hanya dilihat dari aspek legal aspek yang mendewakan mempertimbangkan hak konstitusional warga untuk memilih dan dipilih (right to be vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional melalui mekanisme dan system OMOV (one man one vote), namun mengabaikan multiflier negetif effect dari Dinasti Politik itu di tatanan implemebtasi yang akan cenderung keluar dari tujuan demokrasi itu sendiri secara umum yaitu menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dengan konsep yang mengedepankan keadilan, kejujuran dan keterbukaan.
Jika memang tujuan demokarsi kearah kesejahteraan masyarakat, maka Demokrasi Politik dinasti justru akan bertolak dari tujuan demokari itu sesungguhnya, maka alangkah baiknya kita tidak ikut dan tidak mendukung secara etika berkembangnya Politik Dinasti, melalui gerakan menolak dinasti politik yang dibeberapa daerah termasuk di Propinsi Jambi sudah pernah berkembang Dinasti Politik sebagaimana kita kenal dengan Dinasti Nurdin dan dinasti Manaf, begitu juga di beberapa tempat lain yang juga ditolak secara etika dan moral berkembagnya Politik Dinasti ini.
Mudah-mudahan pada pemilu serentak tahun 2020 ini, politik dinasti tidak akan merebak dan berkembang tentunya adanya gerakan masyarakat untuk menolak secara moral dan etika untuk berkembangnya Dinasti Politik, sesungguhnya Politik Dinasti merupakan pola demokrasi berbungkus pola kerajaan. **